Dialog, Memenggal Jor-Joran
-
By
admin
- March 18, 2022
- Di Atas Kekuasaan dan Kekayaan
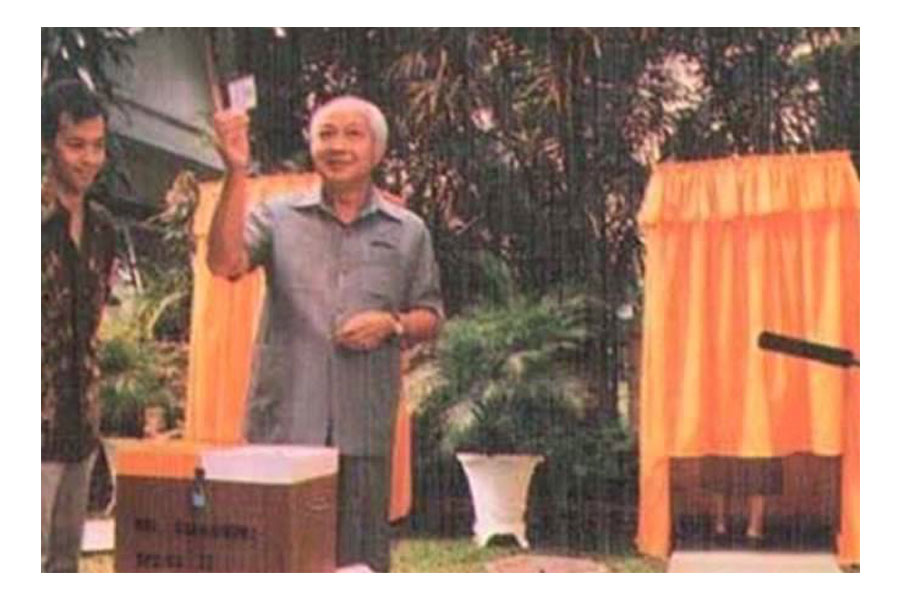
Sebagaimana dinyatakan oleh seorang juru kampanye nasional, masa kampanye itu bukan masa untuk jor-joran, tetapi merupakan kesempatan untuk berdialog dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Pada umumnya memang semua Organisasi Peserta Pemilu (OPP) berusaha untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, bahkan simpati dari sesama OPP.
Simpati berarti menarik hati. Lebih jauh lagi simpati bukan hanya sebatas menyetujui atau ikut merasakan suka duka orang lain, tetapi juga mengandung rasa kasih dan sekaligus tidak mengharapkan orang lain menderita. Buddha menguraikan sedikitnya terdapat empat hal yang menjadi dasar simpati, yakni kemurahan hati, pembicaraan yang ramah, tindakan yang baik, dan melayani semua sesama tanpa membeda-bedakan[1].
Rakyat pemilih akan menaruh simpati kepada OPP yang terbukti murah hati, ramah, baik laku, dan adil, tidak berat sebelah terhadap segolongan masyarakat tertentu. Sikap dan perlakuan yang membeda-bedakan misalnya, mudah menimbulkan prasangka dan merusak simpati.
Tanpa prasangka, membuka diri untuk mendapat simpati, bayangan jor-joran selama masa kampanye tenggelam di bawah keteduhan dialog. Media massa yang mengkomunikasikan secara positif suara-suara juru kampanye dan turut menyerap aspirasi masyarakat membantu mematangkan dialog tersebut. Dialog menjadi omong kosong bila tidak menunjukkan penguasaan konsep dan program. Suara yang bisa jadi simpatik di tengah gemuruh rapat kampanye, menjadi kabur karena kebringasan massa pendukung di jalan raya. Sebaliknya suatu pawai pembangunan atau karnaval yang tertib lebih membuktikan penguasaan program.
Dialog dan komunikasi memang tidak harus menghilangkan perbedaan pendapat. Tetapi perbedaan itu pantas dipahami secara obyektif sehingga tidak menghambat, tidak membangkitkan kebencian atau kedengkian sehingga menutup kemungkinan bekerja sama.
Tercatat dalam kitab Mumonkan (Wu-men kuan), jor-joran antara dua kelompok siswa biksu. Bukan di tengah kampanye pemilihan pengurus atau semacam perwakilan siswa, tetapi mereka memperebutkan seekor kucing. Kucing itu rupanya elok luar biasa. Bisa jadi kenes mengggemaskan lebih dari genitnya seorang wanita, karena mampu mengguncangkan ketenangan kuil perguruan Zen. Para siswa rahib seharusnya tak goyah digoda gadis manis, tetapi kali itu kepincut sang kucing. Binatang itu mereka buru dan tertangkap memang. Lalu terjadilah pertengkaran antara blok Timur dan Barat. Mereka bertengkar, siapa yang akan memeliharanya.
Nansen, sang guru, harus menengahi. Ia memegang leher kucing itu seraya mengacungkan sabitnya. Katanya, jika tidak ada seorang pun dari para siswa itu mengemukakan alasan yang tepat, dalam hal ini maksudnya ‘kata yang baik’, yang mengekspresikan kedalaman penghayatan agama sesuai dengan kelaziman di kalangan Zen, maka kucing itu akan dibunuhnya. Bukankah kucing itu sumber pertikaian? Kucing yang mengeong menjadi kambing hitam. Kambing hitam biasanya juga bukan kambing betulan yang mengembik. Mujur bukan manusia yang menjadi kambing hitam. Ternyata tidak ada seorang siswa pun yang menjawab. Maka Nansen memenggal kucing tersebut menjadi dua bagian. Seekor kucing telah dijadikan korban demi kerukunan dan perdamaian.
Kemudian Nansen menceritakan kejadian itu kepada Joshu Jushin, kepala siswa di kuil tersebut, dan menanyakan pendapatnya. Joshu seketika itu membuka sepatu dan meletakkannya di atas kepala sendiri. Lalu ia pergi. Ujar Nansen, “Kalau saja ada engkau ketika itu, si kucing akan selamat.”
Nansen membunuh kucing, maka ia mencampakkan semua keinginan dengan membasmi obyeknya. Memenggal kucing berarti memenggal semua konflik, menghindari jor-joran atau pertentangan. Namun hanya sebatas itu, tidak lebih dari suatu pedang pembunuh. Sedangkan Joshu menunjukkan adanya Pedang Pemberi Hidup. Ia memilih kasih sayang dan kerendahan hati.
Sangat merendah, dilambangkan dengan menempatkan sepatu yang kotor di atas kepala. Kedamaian menuntut kasih sayang dan kerendahan hati. Sebagaimana dinyatakan antara lain dalam Karaniya Metta Suttatentang mengembangkan kasih sayang: Barangsiapa ingin mencapai kedamaian, ia harus cakap, jujur, tulus, rendah hati, lemah lembut, dan tidak takabur.[2]
Nansen tentunya setuju, memberi hidup sekalipun hanya menyangkut seekor binatang, jauh lebih baik dari membunuh. Bilamana ada Joshu dengan kasih dan kerendahan hatinya saat itu, Nansen, tidak akan membunuh si kucing.
Tidak ada kambing hitam. Tidak ada kucing yang jadi korban. Tetapi jor-joran yang harus dipenggal. Dengan simpati dan kerendahan hati, semua pihak dapat membuka dialog. Dialog punya akar di negeri ini: demokrasi Pancasila.
15 April 1987
[1] Anguttara Nikaya, IV, 3:32
[2] Khuddakapatha 4
