Buku dan Menanam Jasa
-
By
admin
- June 4, 2022
- Keselamatan di Bumi
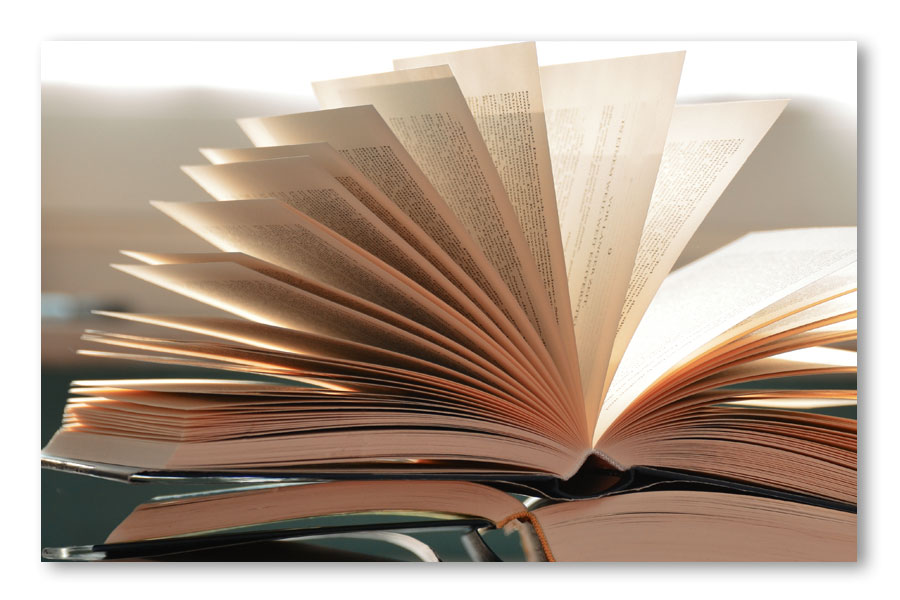
Tidaklah terbayangkan bagaimana kemajuan dunia ini bila tidak ada buku. Setiap pusat pendidikan dan kegiatan mencerdaskan kehidupan manusia memerlukan buku dan perpustakaan. Sebelum ditemukan kertas dan mesin cetak, buku dibuat dari bambu, sutra, kulit kambing, papyrus, atau daun lontar, sehingga penggunaannya sangat terbatas. Kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka dalam bahasa Pali, yang terdiri dari tiga keranjang buku, baru terkumpul dan tertulis secara lengkap seabad sebelum Masehi.
Buddha memang menyampaikan ajaran-Nya secara lisan. Tradisi lisan memberi peluang pada timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu Ia perlu mengingatkan, “Biksu, terdapat dua orang yang salah-menyatakan tentang Tathagata. Siapakah keduanya itu? Ia yang menyatakan apa yang tidak pernah dikatakan atau disabdakan-Nya sebagai sabda Tathagata, dan ia yang mengingkari apa yang telah dikatakan atau disabdakan oleh Tathagata.”[1]
Buddha menyatakan bahwa ketika orang berbicara tentang apa yang diajarkan-Nya, Sutta dan Vinaya haruslah menjadi rujukan untuk membenarkannya. Sutta adalah kumpulan khotbah dan Vinaya semua peraturan atau disiplin yang ditetapkan-Nya. Ada empat kewibawaan besar yang digariskan dalam pengujian apakah betul suatu pernyataan itu berasal dari sabda Buddha. Apabila seseorang mendengar ucapan seorang biksu tentang apa yang diajarkan oleh Buddha, sebagaimana yang telah didengarnya sendiri langsung dari Buddha, tanpa memuji atau mencela, hendaknya ia mencocokkannya dengan Sutta dan Vinaya. Jika tidak ditemukan dalam Sutta dan Vinaya, maka apa yang dikemukakan tersebut bukanlah sabda Buddha, dan mungkin salah dimengerti olehnya, sehingga harus disangkal. Sebaliknya jika ditemukan dalam Sutta dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Vinaya, dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnyalah itu sabda Buddha yang telah dimengerti olehnya dengan baik. Inilah kewibawaan pertama yang harus diakui.
Apabila seseorang mendengar ada yang berkata tentang apa yang diajarkan oleh Buddha, sebagaimana yang didengarnya dari kesaksian sekelompok biksu di bawah bimbingan para sesepuhnya, ia harus mencocokkannya dengan Sutta dan Vinaya. Jika ditemukan dalam Sutta dan Vinaya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnyalah itu sabda Buddha, dan telah dimengerti oleh mereka dengan baik. Inilah kewibawaan kedua yang harus diakui. Mungkin seseorang mendengar dari banyak sesepuh yang menganut atau menjadi pelindung ajaran menurut warisan tradisi. Ia harus membandingkannya dengan Sutta dan Vinaya. Inilah kewibawaan yang ketiga. Demikian pula sikap yang ditunjukkan bila mendengar dari seorang biksu yang mewarisi tradisi. Inilah kewibawaan keempat. Dengan kata lain tidak ada kewibawaan tanpa pembuktian kebenaran berdasarkan Sutta dan Vinaya.[2]
Kapan tepatnya ajaran Buddha mulai ditulis tidaklah kita ketahui benar. Tugu Asoka yang didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi menyebutkan nama sejumlah judul Sutta yang diduga agaknya sudah tertulis pada zaman itu. Namun yang pasti terdapat tiga konsili yang menguji secara sistematis kesahihan ajaran Buddha, dan penulisan lengkap terlaksana pada konsili keempat di abad kesatu sebelum Masehi. Kitab yang ditulis dalam bahasa Pali itu terpelihara keasliannya di Sri Lanka. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta dikenal sejumlah Sutra dan kini sudah banyak yang hilang di negeri asalnya, tetapi masih ditemukan terjemahannya dalam bahasa Tibet, Cina, dan lain-lain.
Para rahib Buddha dari Cina yang melakukan perjalanan untuk mengambil kitab suci ke India singgah di Sumatera dan Jawa. Tercatat antara lain Hui-neng yang menerjemahkan naskah Maha Parinirvana Sutra di bawah bimbingan Jnanabhadra, rahib Jawa. Di Indonesia ditemukan peninggalan naskah dalam bahasa Kawi seperti Sanghyang Kamahayanikan dan Sanghyang Kamahayanan Mantrayana, serta karya sastra Kunjarakarna danSutasoma. Memperbanyak suatu kitab pada masa itu berarti menyalin atau menuliskan kembali, dan sukar dimanfaatkan oleh orang banyak. Sedangkan candi dengan reliefnya bisa berbicara lebih banyak. Dapat dikatakan kitab suci itu di Indonesia tidak tertulis tetapi tergambar sebagai relief sehingga dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat, terpelajar atau pun tidak.
Percetakan secara terbatas mulai dikenal akhir abad kedua, ketika Cina menemukan kertas, tinta, dan kayu yang diukir untuk mencetak. Hasil cetakan tertua ditemukan di Jepang berisi mantera Buddha yang berasal dari tahun 764-770. Buku tertua hasil cetakan Cina pada tahun 868 adalah bagian dari kitab suci yang berjudul Sutra Intan. Cina memang merahasiakan pembuatan kertas. Setelah Eropa mengenal kertas dan menemukan mesin cetak pada abad pertengahan, buku atau barang tulisan mudah dihasilkan sebanyak-banyaknya.
Menyalin atau memperbanyak kitab suci jelas merupakan pekerjaan yang mulia dan membuahkan pahala. Pada abad ke-12, Shotoku, Kaisar Jepang yang diasingkan selama tiga tahun, menghabiskan waktunya selama itu dengan menyalin Lankavatara Sutra, dengan tinta merah yang berasal dari darahnya sendiri. Buku karya kaisar ini berjumlah 135 halaman terdiri dari 10.500 kata. Shotoku melakukannya dengan harapan mendapatkan pahala, sehingga dapat kembali menduduki takhta. Kemudian ia memang kembali berkuasa pada tahun 1144, dan memerintah Jepang selama 20 tahun.
Penerbitan buku di Indonesia belakangan ini berkembang pesat. Namun buku-buku agama Buddha termasuk langka. Hanya sebagian kecil dari Tipitaka yang ditemukan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tidakkah ini peluang untuk menanam jasa? “Lebih besarlah pahala bagi mereka yang memperbanyak Sutra ini, lalu mempelajarinya dan menerangkannya kepada orang lain.”[3]
30 Agustus 1989
[1] Anguttara Nikaya II, 3 : 3
[2] Digha Nikaya 16
[3] Sutra Intan/Vajracchedika Prajna Paramita 15
